SOUL
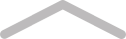
Chapter 1 : Jiwa Yang Terkekang
7 tahun yang lalu, tepatnya ketika Saya berusia 9 tahun. Kebebasan di negara Saya itu mengalahkan yang lain. Sebab, bebas kami berbeda.
Ketika anak kecil berlari, orangtua mereka mengawasi.
Ketika remaja berekspresi, dewasa mengapresiasi.
Ya, itu bebas.
Semua berjalan lancar, cahaya mata setiap orang memancar. Cantik seperti guci antik. Ribuan tahun perlulah untuk membuat negara kami seperti ini. Tega orang itu, jika berani menghancurkannya.
“Tak ada!” kesalahan bagi kami yang berpikir bahwa dunia ini telah damai. Berpikir bahwa kedamaian itu akan dijaga satu sama lain. Ya, fatal sekali.
Sebuah negara besar, dengan harta sebagai nyawanya, dan senjata sebagai dindingnya. Itu lah yang datang, menghancurkan kami.
Saya masih dalam usia 9 tahun, yang masih berlari mengikuti hembusan angin. Justru ditangkap dan dikurung dalam dunia yang kelam.
“Dia akan berguna nanti,” kata-kata yang seharusnya terdengar seperti dukungan, dikatakan dengan maksud menjadi perbudakan. Kasar sekali terdengarnya. Tapi memang begitu yang sesungguhnya. Ketakutan menyelubungi diri Saya saat itu. Tapi, perasaan takut Saya kini telah berubah jadi Gelap.
7 tahun Saya dikurung dalam sel ketakutan. Kini usia Saya menginjak 16. Ulangtahun Saya tak pernah terasa indah. Memang tidak mungkin.
Tidak ada yang tahu, dunia akan seperti apa nantinya. Bahkan penjajah ini.
Hari ini Saya dikeluarkan dari sel. Tangan Saya selalu diborgol, sehingga sulit bagi Saya untuk berdiri. Tidak hanya tangan, jiwa Saya juga dikekang dan dikunci seperti sebagaimana borgol bekerja.
“Cepat!” Ujaran yang benar-benar terasa menyakitkan bagi Saya. Kata yang begitu wajar, diartikan oleh Saya sebagai pemaksaan.
Saya melihat banyak Manusia lain juga bernasib sama seperti Saya. Mereka diikat pinggangnya satu sama lain dipisah jarak tali membentang 120cm. Saya diantaranya.
“Jalan.” Perintah biasa yang terasa menembak jiwa Saya. Jika Saya dan lainnya tidak mengikuti, bisa mati.
Kami dipekerjakan di suatu pabrik. Saya membersihkan mesin pabriknya.
“Yang benar!” Jika Saya diberi peringatan kesalah 5 kali, Saya akan tenggelam dalam keadaan yang lebih buruk.
8 jam sehari, itulah waktu bagi kami bekerja. Tanpa upah.Pabrik yang dibangun negara gila ini adalah Senjata. Mereka sendiri pun senjata. Senjata Jiwa, yang telah bersiap meluncurkan pelurunya pada ribuan jiwa di negri ini.
Yang tersisa dari kami hanyalah jasad dan nyawa, tanpa jiwa dan cahaya. Kosong.
Sepi.
Takut sudah tidak lagi menjadi kata yang mewakili kami.
Sebelum kembali ke sel, Saya dan yang lainnya melewati lorong bata yang gelap dan sunyi. Jendela besar menganga memamerkan pada kami kebebsan yang telah direnggut.
Orang-rang, anak-anak dari negara penjajah ini bermain dibawah gedung kematian ini.
Setiap kali berjalan melewatinya, Saya terasa seperti ditusuk.
Namun, Saya melihat seorang remaja laki-laki. Jika Saya normal dan bebas, mungkin Saya jatuh cinta padanya. Sayangnya, Saya kehilangan seluruh perasaan Saya.Mulai dari cinta sampai benci, Saya kehilangan.
Stres yang membakar kami, membuat tak sedikit dari kami yang gila. Histeris. Mungkin Saya juga gila, dengan ekspresi yang berbeda.
Saya lupa. Lupa bagaimana cara untuk membenci, untuk mencintai,untuk menakuti. Yang Saya tahu hanya Perih.
Terdengar sama saja, namun Perih Saya berbeda. Saya setiap hari merasa Jiwa saya semakin lama semakin hancur. Kehancuran yang menjadi tawa dan kepuasan para penjajah. Hanya itu yang Saya tidak ingin lihat. Saya sudah melihat banyak hal, meski hanya didalam sel, saya melihat banyak yang tidak Anda lihat.
Tapi, jika Saya melihat mereka puas atas kehancuran Saya, Saya tidak mau.
Apa nama perasaan Saya ini? Anda tahu?
Sebab, meski Saya merasa, Saya tidak dapat menerka.
Saya bukannya hidup, Saya hanya tidak mati.
Melewati lorong bejendela besar tadi, saya kembali melihat sosok laki-laki itu. Saya berhenti sebentar. Sadar, Saya menatapnya, laki-laki itu menoleh. Saya terus menatapnya datar. Ia tersenyum. Manis sekali.
Saya kemudian terus berjalan. Mungkin, satu-satunya yang membuat nyawa saya tetap ada disini adalah senyumannya.
Siapa dia? Pertanyaan yang sama dengan Saya.
CHAPTER 2 : Tangan Yang Menyentuh Tanah
Setiap 3 Minggu sekali, Saya dan para Manusia lain dibiarkan bediri di lapangan. Lapangan tempat biasanya Saya melihat laki-laki itu. Penjajah kejam itu sudah merasa baik disaat kami ditempatkan di sana.
Tapi, batin Saya justru tersiksa.
Para remaja berlalu-lalang dengan riang. Bukan negara Saya, tapi mereka.
“Bersyukurlah kalian, masih bisa menghirup udara!”Kata yang selalu penjajah ulangi setiap 3 minggu sekali. Sungguh menyiksa.
Saya dipamerkan bahwa mereka bebas dan Saya tidak.
Pagi yang kesekian kalinya datang. Hari ini Saya dan Manusia terjajah lain mengisi jadwal untuk berdiri di lapangan.
Lelah sekali Saya rasanya.
Saya tidak pernah tidur dan berbaring.
Sebab, jika penjajah datang dan mendapati Saya masih tidur, bukan main hukumannya.
“Bangkit, keluarlah” kata yang ringan tapi menohok. Keluar dari sel, Saya selalu khawatir jika sedetik kemudian Saya akan mati.
Seperti biasa, Saya melihat Manusia lain diikat. Saya juga, tentunya.
Kami berjalan dibimbing penjajah itu ke lapangan. Permainan kasti oleh para remaja sedang tergelar disana.
Oh, bukan main tersiksanya.
“Hirup udara itu, hanya 10 menit kalian disini!” kata itu kemudian disertai tawa. Tawa yang tak riang tapi justru membuat meriang. Jahat terdengarnya.
“Roy, berhenti tertawa, tawamu jelek!” seorang lelaki berteriak sambil disusul tawa. Tawa kali ini riang dan ringan.
Tawa yang Saya dengar adalah tawa laki-laki yang seringkali Saya tatap.
“Heh, lucu melihat mereka yang tak berdaya ini!” balas pria itu.
Seseorang berteriak histeris, “TIDAK!” Jeritan keras dan memekik telinga.
Sudah beribu kalinya Saya mendengar yang seperti ini.
Si peneriak meronta minta dilepas. Wajah remaja yang harusnya masih belajar, justru ingin menghajar orang dihadapannya. Teriakan itu terus bersuara.
Bam!
Tiba-tiba suara itu diam.Gemerincing rantai tak lagi terdengar setelah suara keras keluar beserta peluru perak nan mengkilap.
Saya gemetar. Saya diam. Saya berkeringat.
Mata Saya tak berani menatap kemanapun, Saya hanya mengajukan tujuan mata ke apa yang ada dihadapan Saya.
“Bawalah” ujar pria yang Saya dengar bernama Roy.
Terdengar gemerincing rantai yang terseret.
Saya kembali mengucurkan keringat.
Mereka hina. Mereka jahat dan laknat.
Pikiran Saya hanya bisa berkata demikian.
Benci? Apa itu? Saya tidak tahu. Saya bukannya benci, Saya lebih dari itu. Tidaklah Saya tahu disebut apa perasaan Saya ini.
“Roy…?” lelaki remaja itu menatap Roy dengan pandangan ngeri.
“Tuan Muda, Saya harus melakukannya agar yang lain kapok”
Tuan Muda. Panggilan ini biasa dilayangkan pada seseorang yang merupakan anak dari penjabat tinggi dalam suatu bidang. Tidakkah Saya tepat?
Siapa dia?
Saya menerka dan menerka, tapi Saya tiada pikiran yang mampir memberi jawaban.
Remaja itu setelahnya menatap deretan Manusia yang diikat. Tatapan dalam yang lembut dipantulkannya.
“Roy, maukah kau melepaskan mereka? Hanya untuk 30 menit saja?”
“Tuan Muda, itu―”
“Tak apa, kalau aku, Ayah pasti tak apa”
Siapa Ayahnya? Pikir Saya.
Saya terkejut bukan main. Pria jahat itu melepas borgol kami satu per satu.
“30 menit, Jangan berani beraninya kabur ya”ucapnya.
Satu per satu setelah dilepas, manusia-manusia itu berhamburan menghirup udara dan berlari memutar-mutar.
Saya tak sanggup berlari. Saya menarik nafas dalam dan menjatuhkan diri Saya ke tanah. Tangan Saya meraba rerumputan lembut yang Saya duduki.
Baru kali ini, hanya dengan menyentuh tanah, Saya merasa hidup kembali. Tangan Saya terlalu sering diikat, sehingga borgol itu membekaskan luka. Darah mengalir dari luka tersebut. Tapi Saya sudah tak merasakan sakitnya.
Saya kemudian memejamkan mata dan mendengarkan angin dengan seksama.
“Hey, hanya 30 menit dilepas, kau mau menghabiskan waktumu yang berharga itu hanya dengan menyentuh tanah?”
Apa dia berbicara dengan Saya…? Suara itu adalah suara lelaki yang kerap Saya tatap.
Saya berdiri dan menatapnya dalam.
“Nama,”
“Nama? Namaku? Ah, aku Zen. Kau?”
“Saya… Siapa Saya…?”
Apa kalian bingun dengan jawaban Saya? Tapi Saya sungguh lupa, siapa diri Saya. Nama, bahkan Saya tidak yakin punya nama. Saya mengingat lagi Siapa nama Saya.Sebab disini, kami dipanggil dengan berbagai sebutan kode.
“ARTA11” Saya menyebut kode Saya.
“Kodemu, ya? Ah, sungguh aku tidak pernah setuju dengan sebutan itu. Baiklah berhubung itu ARTA, bagaimana kalau aku memanggilmu Arietta? Terdengar bagus!”
“Saya rasa, Saya tidak cocok untuk nama itu…”
Saya terus berpikir kenapa Zen ini mau berbicara dengan Saya. Bingung dibuatnya.
“Kenapa?”
“Terlalu manis,”
“Bukankah bagus? Cocok kok!”
Saya merasa, itu sama saja dengan berkata bahwa Saya manis. Saya pada akhirnya setuju dengan nama Arietta. Meski Saya terus mencari siapa nama asli Saya.
“30 menit!” teriak sang penjajah jahat. Saya dan para manusia lain ditarik, dan diborgol kembali.
Saya menatap Zen. Zen tersenyum pada Saya. Matanya berkata bahwa Saya tidak boleh khawatir.
Tapi Saya kembali dalam keadaan dimana Saya khawatir sedetik setelah melihat senyum Zen, Saya akan mati.
Chapter 3-Melebur
Saya dan yang lainnya dibimbing kembali ke sel.
Sel kosong yang hanya berisi ranjang dan bendera yang terpajang. Tempat tidur yang bahkan tidak pernah dipakai untuk berbaring.
Saya kemudian mendudukan diri disana, melipat kaki, dan tangan Saya yang terborgol itu memegangi kepala Saya yang tertunduk.
6 Jam, selang waktu yang panjang itu Saya habiskan dengan satu posisi yang tak bergerak sedikitpun. Suasana hening sejak Saya tidak bergeming. Ya, berlalu tanpa suasana baru.
Saya setelah berjam-jam dalam posisi tertunduk, akhirnya mengangkat kepala. Saya mendengar derapan kaki, pelan tapi jelas. Saya takut itu adalah para penjajah tanpa hati.
Saya memejamkan mata takut.
Saya mendengar derapan itu berhenti di depan sel Saya. Apa Saya melakukan kesalahan?
“Hey, hey, Arietta,”
Suara itu, panggilan itu, apakah Zen? Saya membuka mata Saya.
“Apa kau tertidur?”
Saya menoleh perlahan. Zen. Meski hanya siluet bayangan gelap yang menampak, tapi Saya dapat menebak.
“Zen…?”
“Ah, kupikir kau tidur,”
Saya menggeleng.
“Apa yang kau lakukan?” Pertanyaan yang tidak memiliki jawaban.
“Tidak ada.”
“Tak ada?”
“Saya tidak melakukan apa-apa,”
“Kalau begitu, apa yang sedang kau pikirkan?”
“Saya tidak memikirkan apa-apa,”
“Apa kau merasa sesuatu yang buruk?”
“Saya tidak merasakan apa-apa,”
“Eh? Lalu…, apa kau baik-baik saja?”
“Tidak,”
“?”
“Saya tidak pernah baik,”
Bayangan Zen memiringkan kepalanya. Apa dia kebingungan? Saya sepi. Saya kosong, dan bukankah itu tidak dapat disebut ‘baik-baik saja’?
“Arietta…”
“Apa?” Saya menatapnya. “Apa tujuan kamu kesini?”
“Aku… tidak tahu…, ah ya! Apa kau lapar?”
“Saya laparpun, tidak akan berakhir kenyang. Saya kedinginan, tidak akan berakhir hangat. Saya kesepian, tidak akan berakhir bahagia,”
“Kamu kesepian?”
“Apa menurutmu, Saya akan menjawab tidak?”
Zen kemudian terdiam, Saya merasakan tatapannya dalam.
“Sekarang, Saya bertanya… Apa yang dibutuhkan seseorang saat kesepian?”
Zen tidak menjawab sesaat. Sudut mata saya menangkap bayangannya sedang tertunduk.
“Teman,” sesaat kemudian ia menjawab pertanyaan Saya.
Saya berpikir seperti apa teman? Saya rasanya pernah tahu, tapi kemudian lupa.
“Kalau kau kesepian, aku mau jadi temanmu!”
“Teman…?” Saya terkejut dengan perkataannya. “Itu tidak mungkin,”
“Kenapa?”
“Saya tidak pantas… Negaramu menjajah Saya, bisakah Saya sekali lagi percaya pada orang lain?”
“Kamu… tidak percaya padaku?”
“Haruskah Saya menjawab ‘Ya’? Saya sudah lelah, jika mau menyiksa lebih dari ini, lakukanlah tanpa basa-basi.”
“Kamu ini keras sekali ya,”
Saya menatapnya dingin dan bingung.
“Hatimu, keras sekali, ya?” nadanya polos.
“Saya? Kamu bilang Saya punya hati yang keras? Tidakkah kamu pikir, negaramu itu bahkan memiliki hati?” Saya dengan tegas bertanya, menolak pernyataan dari mulu Zen.
Zen terkejut. Ia diam dan bayangannya menghadap kesamping, sambil tertunduk.
“Aku… ingin melakukan sesuatu,”
“Saya pun juga.” “Meski yang ingin kamu lakukan berbeda dengan Saya, tapi Saya ingin melakukan sesuatu selain merasa terjajah.”
Derapan kaki terdengar lagi dari kejauhan.
“Arietta, aku akan mengunjungimu lagi! Para tentara datang! Sampai jumpa!” Zen kemudian berlari meninggalkan sel Saya.
Saya kemudian kembali dalam posisi awal. Tertunduk tak bergeming.
Para tentara menyebar kesel-sel. Satu sel dijaga oleh seorang tentara. Saya dijaga oleh sesosok pria kurus dan pendek. Tidak seperti tentara.
Sadarlah dia, bahwa Saya sedang memperhatikannya.
“Herankah kamu gadis, dengan sosok Saya?” tanya pria itu. Suaranya lembut tak selayaknya seorang tentara.
Saya diam.
Dari obor yang ia pegang, saya melihat wajahnya tersenyum tipis.
Pertanyaan yang terus berperang dengan pertanyaan lain dikepala Saya bertambah parah. Saya menerka, siapa pria pendek, kurus, dan bersuara lembut ini.
“Inginkah kau gadis, merasa hidup kembali walau hanya beberapa jam?”
Pertanyaan itu menerobos hati Saya. Saya terkejut bukan main.
Sebuah tawaran? Atau, hanya gurauan?
“Saya bukanlah tentara,” ia berujar disela tawa.
Saya menatapnya tanpa berkata.
“Saya dihukum dan dipekerjakan sebagai sanksinya,”
“Darimana Anda? Saya tidak pernah melihat,” jawab Saya.
“Saya dari negri seberang. Saya juga ingin kebebasan dan ampunan,”
“Saya paham,”
“Siapa namamu, gadis?”
Saya diam, 10 detik setelahnya Saya menjawab, “Panggil saja Arietta”
Ia mengangguk, “Saya adalah Bhavana.”
Saya mengangguk.
“Saya ingin membebaskan orang-orang disini, Saya kasihan,”
Hati saya terasa bolong. Dunia ini, miris sekali. Padahal dirinya juga menderita, pantaskah ia mengasihani kami? Para penjajah tak berhati itu tak terampuni.
“Sumpah serapah telah saya teriakkan,tapi tak ada yang terjadi,” ujar saya ditengah hening. “Mereka justru semakin kaya,”
“Tidak apa. Mereka kaya harta, miskin hati, di hari pengampunan mereka akan memohon pada kita untuk memaafkannya.”
“Tidak mungkin Saya akan memaafkannya.”
“Gadis, jika itu harus terjadi, maka terjadilah,”
“Anda mau memaafkannya?”
“Salah satu diantara mereka seringkali berbuat baik. Memberi selimut, makanan lebih, dan mengalunkan nada-nada indah dari permainan biolanya,”
“Siapakah dia, Tuan Bhavana?”
“Dia yang termuda, Tuan Muda yang diberkahi hati indah,”
“Zen,” gumam Saya.
“Apa kau takut pada kematian, Arietta?”
“Saya sudah tidak merasakan apapun… Jadi, Saya tidak bisa menjawab,”
Ia tertawa kecil. “Beristirahatlah,” ucapnya.
Saya sudah berpikir, tak mungkinlah Saya tidur. Tapi, salah, Saya malah bermimpi.
Pagi kemudian datang lagi. Saya membuka mata, berharap bisa melihat jelas keluar sel. “Tuan Bhavana…?”
Diluar bukanlah sosok yang Saya lihat kemarin. Beruntunglah Saya terbangun sebelum jam kerja. Sosok yang berdiri didepan sel adalah sosok tentara seperti semestinya.
Setengah jam, waktunya bekerja lagi. Saya dibimbing ke tempat kerja.
Hari ini, Saya diberi tugas membersihkan mesin-mesin digudang. Bersama empat pekerja lainnya.
Di mesin, saya melihat tulisan India. Kebetulan, salah seorang pekerja bisa berbahasa India.
“Teruntuk Tuan Waida, 1720” gadis berparas cantik itu mengartikannya. “Saya pernah dengar tentangnya,”
“Siapakah dia?”
“Seorang sastrawan yang terkenal kejam,”
Sebuah foto terselip di mesin tersebut. Saya menariknya keluar.
“Foto ini,?!” sosok dalam foto itu mirip dengan bayangan Tuan Bhavana.
“Ini Tuan Waida.”ujarnya.
1720, tak mungkinlah dia masih hidup sekarang.
“Naaja,” Saya menyebut nama gadis itu.
“Ya?”
“Apa artinya Bhavana?”
“Roh.”